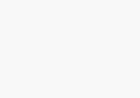H A R I (pe)J U A N G : Hari Pahlawan Nasionalisme Di/Dari Surabaya

Arta Elisabeth Purba
Hampir tiga perempat abad yang lalu saat tepat ketika para diplomat Indonesia sedang berjuang demi kemerdekaan dari kolonialisme Belanda (1945-2019), para pemuda dan rakyat pejuang di kota Surabaya mewujudkan nasionalisme mereka. Komunitas-komunitas para pejuang tersebut bergerak tidak ekslusif berdasar jenis SARA (kelas Sosial, Agama dan RAsial) dan secara revolusioner berani mati mempertahankan kemerdekaan nasionalisme mereka dalam pertempuran hebat pada tanggal 10 November 1945, 74 tahun yang lalu. Aksi dan gerakan revolusioner pemuda dan rakyat Surabaya tersebut berlangsung tidak lebih dari tiga bulan sesudah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17-8-45.
Nasionalisme kepahlawanan di/dari Surabaya kiranya bukan sekedar kenang-kenangan - atau tanda mata, suvenir - dari sebuah masa lalu yang bagaimanapun sudah lewat, “yang sudah hilang.” Saya Sasaki Shiraishi dengan tepat dan benar dalam bukunya Young Heroes. The Indonesian Families in Politics (Ithaca NY: Cornell University 1999 & Jakarta: Gramedia 2001) mengungkap bahwa sifat kejuangan anak-anak muda atau para pemuda sampai pada masa rezim Orde Baru pimpinan “Jenderal Besar” Suharto masih berkuasa tetap revolusioner. Adalah tepat kalau judul buku tulisan Shiraisi - hasil tesis doktoralnya - sebaiknya berjudul “Pejuang-pejuang Muda”; daripada sekedar “Pahlawan-pahlawan Belia.” Maka, aksi, gerakan atau tindakan para pejuang sekitaran tanggal 10 November 1945 - sebagaimana layak dihormati di sebuah Taman Makam Pahlawan - bukan lagi sekedar “yang sudah hilang” tetapi tetap hadir berkobar dalam (sebagian) Young Heroes Indonesia masa kini.
Hari mengingat untuk tidak melupa kobaran api kejuangan revolusioner adalah perwujudan nyata dari keterbayangan nasionalisme anti kolonial di Indonesia yang dicatat dan dikagumi oleh Benedict Anderson (selanjutnya BenA). Terbit awal tahun 1983, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2001, BenA pernah menulis mengapa dan bagaimana rakyat - termasuk pemoeda - “rela mengorbankan nyawa” demi pembayangan atau imajinasi sebuah nasionalisme; yang bukan sekedar fantasi atau khayalan belaka. Perjuangan menghadirkan nasionalisme komunitas-komunitas terbayangkan - meskipun mirip-mirip - tidaklah sama saja dengan keterbayangan berdasar ikatan primordialisme keagamaan yang sering rapuh dan rawan dikait-kaitkan dengan aksi jihad dan gerakan mesianisme, kemartiran iman, Ratu Adil, Imam Mahdi dll. yang sejenis.
Pernah dimuat dan disebar-luaskan oleh media komunikasi massa cetak - berbahasa Inggris lagi! - salah satu perayaan peringatan “10 November” bertema “Street Fashion” berlokasi di Jembatan Merah, Surabaya. Tentu saja “Jembatan Merah” mempunyai kaitan dengan masa lalu peristiwa sebagaiman tercantum dalam foto terlampir dari The Jakarta Post. (gambar foto)
Maka, kisah perobekan bendera tiga warna; merah, putih dan biru berkibar di puncak atas Hotel Yamato Hoteru Surabaya (semula Oranje Hotel dan sekarang Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan No. 65 Surabaya tanggal 29 September 1945 dan pertempuran dahsyat 10 November 1945 adalah sungguh-sungguh peristiwa heroik(!). Pengibaran tersebut dianggap sebagai sebuah provokasi yang dirancang oleh Walikota Surabaya yang diangkat oleh sekutu, Mr. Ploegman guna memantik emosi rakyat setempat yang baru saja dilingkupi euphoria kemerdekaan selama tidak lebih dari dua bulan.
Para pemuda dan rakyat Surabaya sama-sama membayangkan Indonesia sebagai negara merdeka dengan sang saka merah putih sebagai satu-satunya benderanya yang berhak berkibar di atas tanah pertiwi, bukan bendera asing pratanda kembalinya penguasa koloni Hindia Belanda. Olehkarena itu, pelecehan terhadap perjuangan bendera merah putih menyinggung rasa nasionalisme yang membuat orang berani mati kemudian kekuatan digalang untuk memerangi tentara Inggris - sebagai sesama “sekutu” dengan negara kerajaan Belanda. Meskipun pihak sekutu yang berhasil mengalahkan rezim pendudukan militer Jepang (1942-1945).
Sebuah kesengajaan, atau suatu siasat konspirasi, ketika pasukan Inggris berencana memasuki Surabaya, pada 25 Oktober 1945, rakyat Surabaya sudah bersiap hendak perang sehingga Gubernur Jawa Timur berdiplomasi dan hanya memberikan pos-pos secukupnya bagi bala tentara Sekutu - diwakili Inggris. Meskipun semula hanya untuk melakukan perlucutan senjata terhadap Jepang yang kalah perang melawan Tentara Sekutu, namun pada 26 Oktober 1945, pasukan Inggris justru membangun pos-pos perang sehingga pemuda dan rakyat Surabaya berang.
Seruan jihad dari Kyai Hasyim Ashari (kakek Gus Dur) yang disiarkan lewat langar-langgar, masjid dan pengeras suara membangkitkan perlawanan arek-arek Suroboyo yang dibantu kekuatan tentara pada 28 Oktober 1945.
Adalah betul bahwa pembalasan dan “hukuman berat” dilakukan lewat serangan besar-besaran bala Tentara Sekutu pada 10 November 1945 terhadap pemuda dan rakyat Surabaya yang dianggap melanggar aturan perang militer yang berlaku internasional.
Si/Apakah yang sampai masa kini masih memelihara bara api revolusi pemuda - atau arek-arek Suroboyo - dari masa lalu Surabaya, dari 74 tahun silam? Peristiwa demonstrasi mahasiswa dan anak-muda di sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk aksi Gejayan Memanggil jilid I & II di Yogyakarta, 23 September dan 30 September 2019. Perlu diketahui kawasan Jl. Gajayan dikelilingi oleh kampus-kampus: Universitas Katolik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma (didirikan oleh Driyarkara), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Gadjah Mada.
 Tulisan "DPR ASU" dan "SDO PRO WONG CILIK PORA" pada baleho dan dinding pertigaan Kolombo oleh peserta aksi Gejayan Memanggil Jilid I dan II
Tulisan "DPR ASU" dan "SDO PRO WONG CILIK PORA" pada baleho dan dinding pertigaan Kolombo oleh peserta aksi Gejayan Memanggil Jilid I dan II
Bagaimanapun juga, demonstrasi kaum muda masa kini seperti berlangsung di #Gejayan Memanggil telah di/terjadikan - dipicu, dipahami, di-“aku”-i ,dan dimaklumi - dengan aksi-aksi juang kerakyatan; yang dalam kata-kata Bung Karno adalah sebagai “Penyambung Lidah Rakyat.”
Entah itu kepemimpinan Kyai NU Hasyim Ashari, atau Bung Tomo (tokoh orator perjuangan), atau para komandan beberapa Laskar Rakyat, dll. yang tidak “baperan” (akibat tak ada kemandirian) dan juga tidak “mageran” (akibat hanya punya pamrih egoisme) sebagaimana terungkap dari beberapa poster, spanduk dan grafiti yang bukan sekedar sebuah bahasa kosong. Saya Shiraishi, sekali lagi dari kutipan bukunya, “adalah bahasa kosong Orde Baru yang membutuhkan Bapak; tidak sebaliknya.” Sebuah bahasa kosong tanpa kuasa kata-kata yang hanya suka mengatakan ”ya begitulah”.
 Jl Moses Gatotkaca lokasi Aksi Gejayan Memanggil
Jl Moses Gatotkaca lokasi Aksi Gejayan Memanggil
Saat dan tempat demonstrasi yang tanggap dengan seruan undangan #Gejayan Memanggil - sebuah kebetulan (?) - “dimainkan” berhadap-hadapan dengan “penampakan” patung Driyarkara di Jalan Affandi, dulu Gejayan. Patung pemikir filsafat itu ada di samping gedung Auditorium USD, yang bersebelahan dengan Jalan Moses Gatotkaca (nama “pahlawan” korban kekerasan aparat di saat Reformasi Mei 1998 di Jogja), dan berhadap-hadapan berseberangan jalan dengan lokasi gedung bertingkat “Plaza UNY”.
 Mahasiswa demonstarasi di depan patung Driyarkara (Pendiri USD)
Mahasiswa demonstarasi di depan patung Driyarkara (Pendiri USD)
Buah pikiran Driyarkara dikenal dari kuasa kata-katanya untuk jeli dan waspada terhadap permainan dan homoludens: manusia yang senang bermain-main. Kita membaca dari kata-katanya yang sangat terkenal, “Bermainlah dalam permainan tetapi janganlah main-main! Mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi”.
 Mahasiswa demonstarasi di depan patung Driyarkara (Pendiri USD)
Mahasiswa demonstarasi di depan patung Driyarkara (Pendiri USD)
Hari (Pe)Juang tanggal 10 November 2019 dari para “young heroes” nasionalisme negara bangsa Indonesia adalah juga sepantasnya untuk dirayakan sebagai kelanjutan dari peristiwa dua bulan sebelumnya di banyak kota di Indonesia, termasuk perhelatan #Gejayan Memanggil di Jogja.