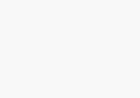Impian Turunnya Soeharto

Yunanto Sutyastomo
Dua puluh tahun setelah turunnya Presiden Soeharto seolah negeri ini tidak pernah berhenti dari berbagai persoalan. Padahal ketika itu banyak impian dari turunnya Soeharto, kehidupan demokrasi diharapkan lebih baik, demikian pula kehidupan ekonomi kita akan lebih bagus dari era Orde Baru, tetapi impian itu semakin lama semakin menjauh. Ketika generasi awal reformasi sudah tidak lagi berusia muda, dan memilih melanjutkan kehidupan yang lebih mapan, persoalan – persoalan tidak pernah berhenti di negeri ini. Tiba – tiba kita dikejutkan ada demontrasi para mahasiswa di berbagai kota pada bulan September 2019, demo yang awalnya hanya terjadi di beberapa kota ini kemudian menjadi protes yang bersifat nasional, serentak dan sontak menunjukan kalau pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pasca reformasi masih menumpuk sekian banyak, bahkan bertambah pula. Sebelum demonstrasi mahasiswa ini terjadi, kita dikejutkan dengan demonstrasi saudara – saudara kita di Papua, benang kusut persoalan Papua juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dari dua kasus tersebut sebenarnya kita diajak untuk melihat kembali perjalanan bangsa ini, apakah letupan – letupan itu hanya bersifat insindetal atau memang hal ini terjadi akibat akumulasi persoalan yang tak pernah tuntas. Kalau kita lihat setelah tahun 1998 terjadi peralihan kekuasaan politik di negeri ini, secara nyata terjadi perubahan kepemimpinan nasional secara berkala dengan pemilihan presiden dan legislatif selama lima tahun sekali. Perbincangan kita tidak akan berbicara mekanisme atau cara pemilihan tersebut, tapi hal yang terpenting dari kepemimpinan di Indonesia adalah salah sumber dari korupsi yang terjadi secara masif di negeri ini. Korupsi yang dimaksud tentu saja bukan semata persoalan uang, tetapi juga terjadinya pola kepemimpinan yang nepotis, baik kepemimpinan yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Pemilihan umum melahirkan keluarga – keluarga yang secara politik memegang kekuasaan, mereka memiliki pengaruh dan modal untuk terus berkuasa, sirkulasi kepemimpinan hanya terjadi di antara para anggota keluarga, ada anggota keluarga yang bapaknya bupati atau walikota, sementara anaknya jadi pemimpin parlemen lokal, atau suaminya walikota, istrinya ketua DPRD, tidak hanya itu saja, bahkan proyek – proyek pembangunan menjadi bancakan para keluarga penguasa serta para kroni.
Korupsi ini melewati batas – batas yang tidak pernah kita bayangkan, kita bisa melihat mereka yang korupsi berjamaah bisa beda partai politik, beda etnis, beda agama, bahkan kita tidak akan menduga bahwa yang terkena kasus korupsi bersama dalam panggung politik merupakan lawan politik. Lalu pertanyaan buat kita, bagaimana menghentikan ini semua ? Korupsi sudah semacam kanker, ketika kanker itu menjalar, dan kita mengobati satu bagian tubuh yang terkena kanker, maka bagian yang lain masih terdapat kanker yang sama ganasnya. Korupsi memang sudah ada sejak dahulu, tapi bukan berarti tidak bisa dihilangkan, seperti halnya penyakit yang dulunya tidak ada obatnya, tapi kemudian ada pilihan – pilihan untuk menghilangkannya. Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia juga didorong karakter masyarakatnya yang patriaki, masyarakat Indonesia melihat para pemimpin, terutama pemimpin baru, muda dan punya banyak gagasan layaknya Ratu Adil yang akan membawa kita pada masa kejayaan di masa mendatang, tapi semangat itu tidak dibarengi dengan sikap kritis terhadap kekuasaan, ada kecenderungan untuk memuja, tanpa menyadari kalau kekuasaan itu rentan terhadap korupsi. Hal inilah yang sebenarnya berkembang di jaman Orde Baru, dengan kemampuannya Orde Baru mampu menyihir jutaan masyarakat untuk tidak kritis, dan mengkultuskan Orde Baru, baik kelembagaan maupun figur kepemimpinan. Ini yang menjadi virus di seluruh Indonesia, sayangnya virus kemudian bertransformasi sampai sekarang, ibarat ulat sutra yang mengalami berbagai musim, dan menjadi kepompong sampai berubah kembali menjadi kupu – kupu, maka korupsi di Indonesia analoginya seperti itu. Korupsi tidak berhenti, hanya mencari jalan yang kira – kira bisa membuatnya aman, dan ketika situasi kembali seperti dulu, korupsi akan tumbuh berkembang sedemikian rupa.
Romo Budi Susanto menyebut tentang nasionalisme, dan mengutip Ben Anderson, saya tidak akan menulis tentang nasionalisme yang dimaksud Romo Budi, tapi kenyataannya nasionalisme dipakai oleh negara untuk menjadikan dirinya tetap ada, tapi di sisi lain nasionalisme jatuh menjadi slogan dan menjadi tameng suburnya korupsi di Indonesia. Atas nama nasionalisme dan pembangunan, korupsi menjalar ke seluruh pelosok negeri. Lembaga seperti KPK bahkan tidak mampu mengatasi korupsi yang sudah menjalar ini, apalagi kalau revisi UU KPK jadi dipakai, maka korupsi semakin menjalar. Nasionalisme yang dikatakan oleh Ben Anderson sebagai mimpi bersama itu memang akhirnya jadi mimpi bersama bagi elite politik, oligarkim politik dan kartel politik di Indonesia, maka jangan heran kalau pemilu sebagai bentuk proses demokrasi di Indonesia tidak serta merta mengubah Indonesia menjadi lebih baik.