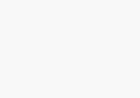“#GEJAYAN MEMANGGIL” (SI)APA?
Apakah aksi Gejayan Memanggil Jilid I dan II merupakan gaung dari peristiwa kekerasan dan kekejian di kawasan Gejayan yang terjadi 21 tahun silam pada Jum’at, 8 Mei 1998?

Aksi demonstratif “#Gejayan Memanggil” pada Senin, 23 dan 30 September 2019 telah berlalu. Adalah penting untuk melihat kembali apakah hal itu merupakan gaung dari peristiwa kekerasan dan kekejian di kawasan Gejayan yang terjadi 21 tahun silam pada Jum’at, 8 Mei 1998? Dalam peristiwa yang menewaskan salah seorang mahasiswa - kalau belum melupa untuk ingat, namanya Moses Gatotkaca - yang namanya kemudian diabadikan pada sebuah jalan di samping Hotel Radisson Yogyakarta (kini bernama Yogyakarta Plaza), saat itu Gejayan telah menjadi sebuah pelajaran sejarah. Bahkan berkat peristiwa itulah, sesungguhnya yang konon dinamakan Pisowanan Agung Rakyat Yogyakarta di Alun-alun Utara bersama Sultan Hamengku Buwana X dan Paku Alam VIII pada Rabu, 20 Mei 1998, tepat sehari sebelum Presiden RI Soeharto mengundurkan diri, dapat terjadi. Padahal peristiwa 20 Mei 1998 sebenarnya merupakan sebuah upaya konsensus negosiatif di antara para aktivis mahasiswa, baik dari UGM, UIN, USD, dan ISI, untuk menemukan saat dan tempat yang tepat sebagai titik kumpul demi aksi bersama atas nama rakyat, pemuda dan mahasiswa demi Reformasi Indonesia.
Bagi masyarakat Yogyakarta masa kini, bahkan historisitas Jalan Gejayan, bahkan sekarang sudah diganti menjadi Jalan Affandi, tampak sekadar tercermin dari Jalan Moses Gatotkaca belaka. Jalan yang telah menjadi kawasan sentra bisnis telepon genggam dan sudah tidak perlu diingat-ingat lagi sebagai bagian dari sejarah Reformasi di Indonesia. Aksi “#Gejayan Memanggil” yang dihadirkan dengan gaya dan tujuan yang berbeda dengan gerakan mahasiswa 1998 semakin menampakkan ada sebagian unsur yang hilang dari pergerakan pemuda Indonesia di masa kini. James T. Siegel (“Pikiran-pikiran Awal tentang Kekerasan 13 & 14 Mei 1998 di Jakarta”) sudah waspada dan jeli bahwa aksi mahasiswa 1998 telah dicampuri proyeksi dari para orang tua mereka yang adalah kelas menengah dan khawatir dengan krisis moneter (“krismon”) yang sedang menghantui. Sebagian mahasiswa yang rela berpanas-panas untuk turun ke jalan, bahkan merasakan pedihnya kena gas air mata, sebenarnya tidak serta merta membela nasib teman-temannya yang mati tertembak peluru aparat keamanan. Apalagi mengatasnamakan rakyat, yang justru dituduh sebagai massa perusuh dan penjarah di Jakarta pada waktu (rejim milik) Suharto harus tumbang. Maka tak heran jika rakyat selalu hilang dari pikiran para mahasiswa aktivis yang berani menghadapi aparat bersenjata lengkap, tetapi berjarak dengan massa yang terlanjur merusak dan menjarah.
Jadi, jika dalam aksi “#Gejayan Memanggil”, bertebaran banyak kata, khususnya yang berbahasa eksklusif “Jawa ngoko” seperti “Sido pro wong cilik pora?, “DPR ki malah piye”, “Asline mager pol, tapi piye meneh? DPRe pekok”, sebenarnya pesan (si)apa yang ingin digaungkan? Bahkan, ada pula yang berkata-kata, “Skincare mahal gak papa buat panas2an. Lebih mahal NKRI soalnya”, bukankah hal itu hanya menjadi semacam penghibur(an) belaka lantaran merasa kecapekan dan kepanasan akibat baru pertama kali berjalan di sepanjang jalan Gejayan? Dan yang menarik, pada Senin, 30 September 2019, ada sebuah tulisan yang berbunyi: “Almost God Wiranto” yang terpampang di sebuah billboard di lampu lalu lintas pertigaan Colombo, Gejayan (The Jakarta Post, Sep. 30, 2019); sementara itu, beberapa hari berikutnya, pada Kamis, 10 Oktober 2019 dikabarkan Menko Polhukam Wiranto ditusuk di bagian perut di dekat pintu gerbang Lapangan Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Hanya kebetulankah?